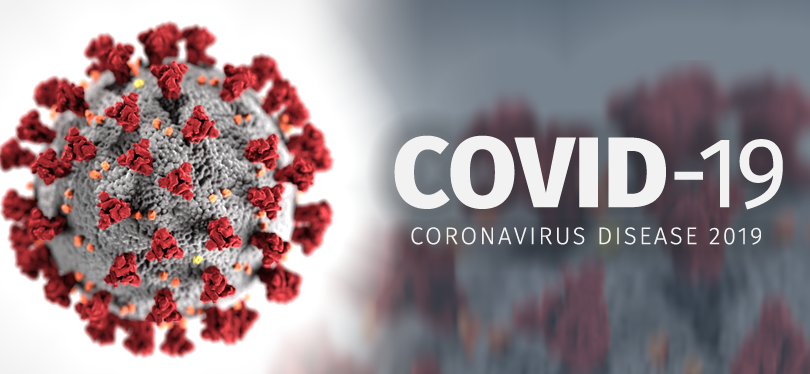Jakarta - Accepted. Ya, itu adalah kata yang sangat sakral dan ditunggu-tunggu bagi siapapun yang sedang submit sebuah jurnal. Kita bisa berjingkat kegirangan saat ada surel masuk bertuliskan kata sakti tersebut. Tidak bisa dipungkiri bahwa pembahasan terkait dunia publikasi jurnal ini tidak ada habisnya dan masih dianggap "seksi" bagi siapapun yang terjun di kancah "persilatan" akademisi, di antaranya motivasinya faktor kewajiban dalam mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, faktor kebanggaan karena mendapat "legitimasi" sebagai seorang ilmuwan, juga mungkin terkait dalam hal mengerek kenaikan jabatan yang berimbas pada perbaikan ekonomi.
Di mata sang idealis, tentu semua itu juga berkontribusi dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia. Sayangnya, semangat yang begitu heroik tersebut sering tersandung dengan mahalnya biaya publikasi jurnal. Tidak heran, masih sangat banyak kita jumpai seorang dosen yang sudah mengabdi belasan bahkan puluhan tahun, tapi jumlah publikasinya bisa dihitung jari, bahkan banyak juga yang jalan di tempat. Jadi sampai lebaran kuda pun jangan harap bisa menyandang gelar profesor tanpa adanya publikasi jurnal ini.
Dalam aturan Pedoman Operasional/Penilaian Angka Kredit (PO-PAK) Kemendikbud, sangat jelas porsi kewajiban penelitian ini sangat besar yakni antara 25%-45% tergantung jabatan fungsionalnya. Sedangkan kita tahu, salah satu produk penting dari sebuah penelitian adalah publikasi jurnal.
Jurnal sangat banyak macamnya, dari mulai jurnal kelas "gurem" sampai dengan jurnal kelas "tier tinggi" alias Jurnal Internasional Bereputasi. Rata-rata jurnal ini bersandar pada lembaga pengindeks Scopus dan Web of Science, sedangkan untuk jurnal lokal berkiblat pada lembaga Sinta.
Harus diakui, produktivitas karya ilmiah para ilmuwan di negara kita masih tergolong rendah. Menilik dari website lembaga pemeringkat terkemuka yakni Scimagojr, Indonesia cuma berada di peringkat ke-45 di dunia, bahkan di kancah Asia Tenggara pun kita masih kalah dari Thailand, Singapura, dan Malaysia. Jadi masih jauh panggang dari api, padahal kita memiliki potensi di atas mereka.
Kenapa fenomena ini bisa terjadi? Salah satu yang paling besar pengaruhnya adalah karena mahalnya biaya publikasi ini. Coba kita telisik lebih dalam kenapa publikasi Jurnal Ilmiah Bereputasi ini dikatakan mahal.
Harga dalam sebuah jurnal dikenal dengan istilah Article Publishing Charge (APC). Sebagai contoh, harga APC (tier Q1) dari Jurnal Internasional Bereputasi:
-Nurse Education Today USD 4.090 = Rp 58.7 juta
-International Journal of Nursing Studies USD 4.470 = Rp 64.1 juta
-Journal of the American Medical Directors Association USD 4.370 = Rp 62,7 juta
Dan, masih banyak jurnal lain, yang mayoritas berharga di angka puluhan juta rupiah. Bagi seorang dosen yang bekerja di luar negeri yang digaji dengan dolar, mungkin APC ini tidak akan jadi sebuah masalah, dan tinggal "sat set sat set". Tapi bagi seorang dosen yang tinggal di Indonesia dengan gaji rupiah, nominal tersebut tentu sangatlah fantastis. Bayangkan harga dari sebuah jurnal saja, jika dikonversikan terhadap gaji seseorang yang berbasis UMR, itu sudah setara dengan gaji 2 tahun penuh, belum lagi kalau terkena pajak penghasilan.
Apakah ada jurnal yang gratis? Jawabannya ada. Memang betul ada yang gratis, Tapi, perlu diperhatikan Jurnal Internasional Bereputasi yang gratis sangatlah sedikit; anak muda mengenalnya dengan istilah "barang ghaib". Jadi begini, mayoritas Jurnal Internasional Bereputasi menerapkan open access; semua orang bisa download dan membaca paper jurnal kita dengan cuma-cuma alias gratis.
Kalau begitu siapa yang menanggung beban biaya operasional dari si penerbit jurnal? Jawabannya, Ya jelas kita yang submit ke jurnal tersebut. Jadi itulah alasan kenapa mayoritas jurnal berbayar. Banyak yang beralasan semua itu karena ada kartel bisnis di dalamnya. Begini saja; coba dipikirkan: sebuah penerbit jurnal mengakomodasi ribuan paper yang di submit oleh para peneliti di seluruh dunia. Jelas ini akan membutuhkan cost operasional yang tidaklah murah bukan?
Jika berbicara soal jurnal gratis, saya analogikan sebagai "sebuah pintu"; ukuran pintu ini sangatlah kecil dan jumlahnya sedikit, sedangkan yang mau masuk saja butuh antrean panjang dan berjibun. Otomatis kita menjadi sangat sulit bergerak dan akan terjadi "baku hantam" dalam prosesnya. Belum lagi masalah ketidaksesuaian topik penelitian kita dengan jurnal tersebut.
Apakah pemerintah perlu untuk turun tangan dalam pembiayaan APC ini? Jelas sangat perlu, karena kalau hanya mengandalkan kantong pribadi seorang dosen, maka hal itu adalah mustahil. Dari pihak kampus memang biasanya menyediakan bantuan publikasi, tapi ini sifatnya pun terbatas dan harus berkompetisi terlebih dahulu dengan rekan sejawat. Dan, perlu diingat juga, masih banyak juga kampus kampus kecil lain yang mengalami keterbatasan pendanaan ini.
Jurnal-jurnal bereputasi memang mahal, tapi mahalnya sebanding dengan tingkat reputasi yang dijaganya. Siapapun para peneliti, walaupun katakanlah punya dana melimpah, tapi jika kualitas publikasinya tidak berkualitas, ya tidak akan pernah bisa masuk ke jurnal jurnal bereputasi tersebut.
Jurnal bereputasi ini sangat kredibel dan ketat dalam menerapkan peer-review, bahkan mayoritas mereka menerapkan double-blind review. Jadi tidak ada celah lagi. Kecuali submit-nya ke jurnal abal-abal atau bahkan terperosok ke jurnal "predator". Itu namanya zonk, jurnal fraud --uang hilang dan jurnal kita tidak ada nilainya.
Kita semua tahu bahwa Indonesia butuh pemerataan sumber daya manusia yang berkualitas. Sokongan penuh dari pemerintah akan menambah daya dorong dalam mengakselerasi produktivitas karya-karya ilmiah ilmuwan Indonesia.
Yayu Nidaul Fithriyyah, S.Kep, Ns, M.Kep dosen PSIK-FKKMK UGM
Baca artikel detiknews, "Balada Dosen dan Publikasi Ilmiah" selengkapnya https://news.detik.com/kolom/d-6022967/balada-dosen-dan-publikasi-ilmiah.
Download Apps Detikcom Sekarang https://apps.detik.com/detik/
Sumber : https://news.detik.com/kolom/d-6022967/balada-dosen-dan-publikasi-ilmiah